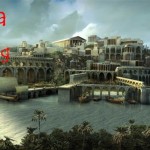Berbicara soal masyarakat Indonesia, kita tentu tahu betul betapa beragamnya suku-suku yang ada. Di Indonesia sendiri, istilah ‘pribumi’ biasanya digunakan untuk mengacu pada identitas asal daerah seseorang. Contohnya, orang Sunda itu ada di Jawa Barat, Orang Bugis itu di Sulawesi, dan seterusnya.
Mengenali suku dan asal usul diri tentu bukan hal yang salah. Justru merupakan hal yang baik bisa mengenali identitas diri sendiri. Namun sayangnya, terkadang identitas ini justru digunakan untuk membedakan mereka yang penduduk asli dan pendatang pada daerah tertentu. Jika memang ingin mengetahui asal-usul penduduk nusantara, maka kita harus mundur cukup jauh kurang lebih 100 ribu tahun yang lalu.
1. Pendatang pertama Nusantara, Melanisia
Menurut teori sejarah, yang pertama datang dan tinggal di tanah nusantara sebenarnya adalah homo erectus yang datang sekitar 1,5 hingga 1,7 juta tahun yang lalu. Namun kelompok-kelompok mereka akhirnya punah kira-kira pada 100 ribu tahun yang lalu. Selanjutnya, barulah homo sapiens atau manusia modern memasuki nusantara.
![Area Melanisia [Image Source]](https://boombastis.sgp1.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2015/09/Area-Melanisia.jpg)
Manusia pertama yang datang ke nusantara ini memiliki ciri-ciri Melanosoid atau golongan etnis Negrito, yaitu seperti orang Papua dan Aborigin. Para manusia ini menempati nusantara hingga zaman es berakhir dan es mencair menjadi lautan yang memisahkan pulau dan terbentuklah Indonesia seperti sekarang ini. Suku-suku dengan etnis Negrito yang ada di Indonesia ini antara lain Suku Dani, Bauzi, Asmat, dan Amungme.
![Suku Dani [Image Source]](https://boombastis.sgp1.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2015/09/Suku-Dani.jpeg)
2. Gelombang Kedatangan Kedua (Melayu-Austronesia)
Gelombang kedua manusia modern yang datang ke Indonesia adalah rumpun Melayu dan Austronesia. Rumpun ini mencakup suku Melayu, Formosan, serta Polynesia. Rumpun ini memiliki ciri-ciri wajah bulat, hidung lebar, rambut hitam tebal sedikit bergelombang dan kulit kecoklatan.
![Fitur wajah Austronesia [Image Source]](https://boombastis.sgp1.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2015/09/Austronesia.jpg)
Rumpun Melayu yang masuk ke Nusantara terbagi menjadi dua yaitu Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Melayu adalah mereka yang sudah berhasil menciptakan masyarakat yang stabil sehingga tidak lagi melakukan mobilisasi penduduk. Karena itu, mereka menetap di tempat terpencil dan jauh dari golongan lain sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi percampuran gen. Golongan Proto Melayu ini misalnya adalah suku Nias dan Dayak.
![Suku Dayak [Image Source]](https://boombastis.sgp1.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2015/09/Suku-Dayak.jpg)
Dalam masa peralihan melanesia ke Austronesia hingga zaman manusia mengenal tulisan, jejak kebudayaan maupun ciri fisik masyarakat Melanesia sudah tidak ada lagi di pulau-pulau bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, maupun Lombok. Sementara di wilayah Indonesia Timur, masih terekam gen Melanesia yang sudah bercampur dengan rumpun Austronesia. Sedangkan suku Melanesia yang masih asli adalah mereka yang menetap tanpa gangguan di pedalaman Papua dan masih setia dengan kehidupan dan kebijaksanaan lokal seperti berburu binatang, berkebun dalam skala kecil, serta hidup dalam masyarakat kesukuan.
3. Kedatangan Sino-Tibetan, Dravida, dan Semit
Seribu tahun setelah kedatangan etnis Melayu, peradaban Austronesia juga berkembang pesat dan melakukan interaksi dengan pedagang dari kebudayaan lainnya termasuk Dong Son dari Vietnam. Interaksi perdagangan terus berkembang di awal abad Masehi sehingga masuklah peradaban Dravida, Sino-Tibet, dan Semit.
![Fitur wajah Sino Tibetan [Image Source]](https://boombastis.sgp1.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2015/09/Sino-Tibetan.jpg)
![Fitur wajah Dravida [Image Source]](https://boombastis.sgp1.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2015/09/Dravida.jpg)
Etnis Dravida datang secara bertahap seiring dengan semakin berkembangnya perdagangan di Nusantara. Pengaruh budaya Dravida (India) ini juga terlihat jelas dengan corak kerajaan Hindu di awal abad masehi. Sementara itu, etnis Semit datang pertama kali pada abad 7 Masehi untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Sama dengan Dravida dan Sino-Tibet, penduduk etnis Semit juga banyak yang memiliki menetap dan membaur dengan masyarakat lokal sehingga menambah keberagaman nusantara.
![Fitur wajah Semit [Image Source]](https://boombastis.sgp1.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2015/09/Fitur-ras-Semit.jpg)
Jika definisi pribumi merujuk pada manusia modern pertama yang datang ke Nusantara, maka jawabannya adalah rumpun Melanesia atau yang sekarang merupakan suku-suku di Papua. Jadi, pada hakikatnya nenek moyang semua manusia yang ada di Indonesia itu adalah pendatang. Bumi Indonesia dulunya adalah tanah tak bertuan sampai para pendatang mengklaim tanah tersebut milik mereka dan melewati kekuasaan para penjajah hingga kini bisa menjadi negara Indonesia yang multikultur. Jadi, tidak tepat rasanya jika sampai sekarang kita masih saja membeda-bedakan satu sama lain berdasarkan ras atau etnis mereka.